KOMENTAR: Iktibar, pengajaran untuk anak muda dari hikayat Nakhoda Muda
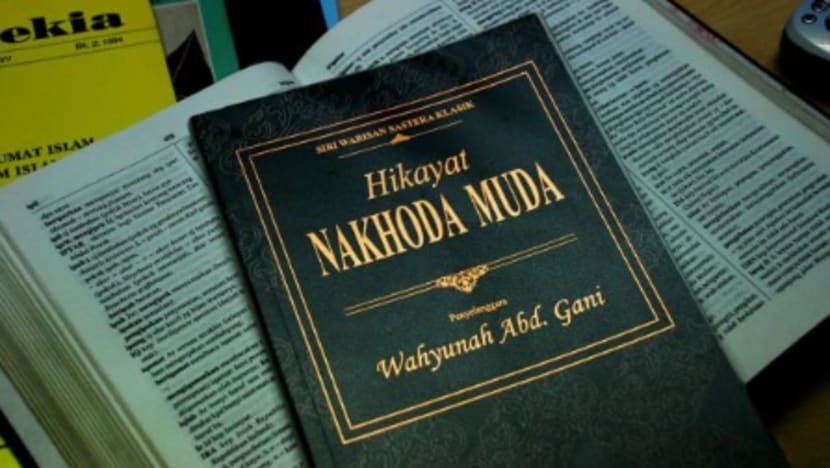
Buku Hikayat Nakhoda Muda. (Gambar: Laman WordPress Psittacula Alexandri)
BERITAmediacorp: Di Nusantara, genre hikayat menjadi rakaman bukan sahaja berkenaan cerita penglipur lara tetapi juga hikayat berkenaan riwayat seorang tokoh yang ditulis oleh penulis sendiri seperti Hikayat Abdullah ataupun oleh orang lain seperti Hikayat Nakhoda Muda yang tersempurna ditulis pada 1763M.
Menariknya sedari awal karya ini mendapat perhatian.
Pasti kerana keunikan karya ini, William Marsden telah menterjemah karya ini dan siap terbit di London pada 1830 dengan diberikan judul Memoirs of a Malayan Family. Malah Munshi Abdullah juga pernah menyebut karya ini sebagai sebuah manikam. Pastilah juga kerana isinya yang kelak nanti menginspirasi Munshi untuk menulis riwayat beliau, yakni Hikayat Abdullah pada 1845.
Nakhoda Lauddin, penulis hikayat ini merakam sebuah riwayat keluarga pedagang pribumi yang akhirnya jatuh akibat dari dasar kolonial Belanda yang mahukan monopoli ke atas komoditi lada hitam. Ayah beliau, Tayan juga dikenali sebagai Nakhoda Muda. Ninda beliau bernama Nakhoda Mungkuta dan keluarga pedagang inilah yang turun-temurun mengerjakan ladang lada hitam sebagai barang dagangan.
Gelaran Nakhoda yang terpakai di Nusantara merujuk kepada pedagang atau pemodal yang pastinya memiliki kapal dagang, suatu pengangkutan utama di rantau yang berkepulauan ini. Mereka adalah segelintir kelas pedagang atau kadang disebut Orang Kaya, yang giat berniaga, selain kelompok istana yang berdagang terus dan mengenakan monopoli ke atas tanaman atau barang dagangan tertentu.
Sebagaimana aturan perdagangan di rantau ini, komoditi utama yang mendapat permintaan tinggi harus dahulu dijual kepada penguasa tempatan sebelum ia dijual nanti kepada pedagang Eropah.
Sultan Banten meraih untung besar dari aturan perdagangan sebegini, sedangkan Belanda terus mahu memastikan mereka mendapat monopoli agar pusaran perdagangan tidak terlepas ke tangan saingan mereka, yakni kompeni Inggeris yang sudah bertapak di Bengkulu, Sumatera.
KEHADIRAN TANGAN GHAIB
Dari rentetan cerita, dikisahkan keluarga Nakhoda Muda yang makmur berdagang akhirnya ditumpaskan oleh penguasa Belanda yang mahu memastikan monopoli mutlak ke atas hasil lada hitam.
Tangan ghaib di sebalik pergeseran Nakhoda dengan Belanda adalah penguasa feudal pribumi sendiri yakni Sultan Banten.
Inilah yang sering terjadi di rantau ini. Runtuhnya kelas pedagang tempatan bukan saja akibat monopoli kolonial tetapi juga percaturan politik dalam kalangan penguasa feudal yang terus bersaing mendapatkan sumber dan kekuasaan.
Kesultanan Banten yang terletak di Jawa Barat adalah antara kuasa utama di daerah itu sebelum akhirnya Belanda menguasai sepenuhnya pada abad ke-19.
Karya ini menarik dalam beberapa hal.
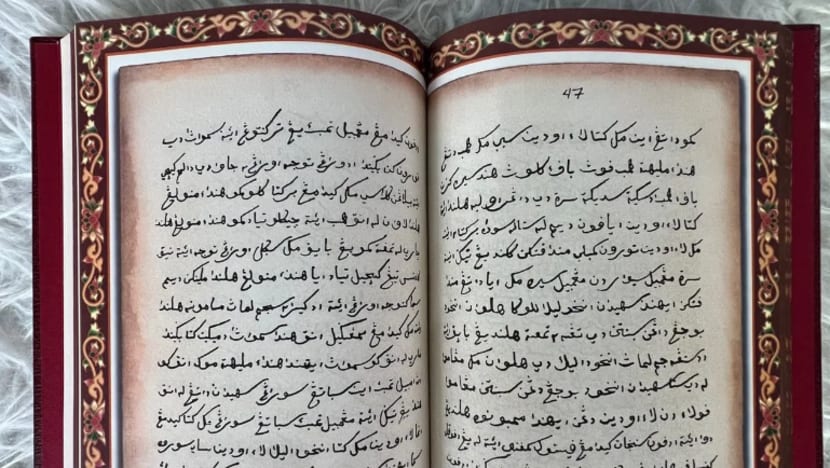
Lauddin anak bongsu kepada Nakhoda Muda, mendapat didikan menulis dan membaca, kerana itulah yang diberatkan oleh ayahnya. Pada zaman itu kemampuan menulis yang terdapat pada segelintir kecil ahli masyarakat. Kerana keluarganya orang berada, maka akses kepada membaca dan menulis tersedia baik.
Nakhoda Muda membuka ladang lada hitam di Semangka dan hasilnya dijual kepada Sultan Banten sehingga khidmat beliau ini dianugerah gelar Kiai Demang Purwasedana oleh Sultan.
Semangka terletak di daerah Lampung, yang terpisah dari Banten oleh Selat Sunda. Tanah yang dibuka di Semangka ini dikerjakan oleh kurang lebih 400 orang Melayu, yang memandang tinggi Nakhoda sebagai ketua mereka.
LADA HITAM JADI REBUTAN
Disebut dalam hikayat ini harga lada hitam dijual kepada Sultan Banten sebanyak dua belas rial sebahara, yang kemudian Sultan menjual kepada kompeni Belanda sebanyak dua puluh rial sebahara. Sultan melarang sesiapa yang berurusan terus dengan Belanda tanpa izinnya:
“Jikalau Kompeni membeli sendiri kepada perwatin ataupun nakhoda-nakhoda, tiada jadi jikalau tiada suka Sultan Banten. Pasti digantung hukumnya, jikalau barang siapa yang membuat perbuatan itu. Kerana lada itu di dalam suka Sultan maka boleh Kompeni Holanda membeli…”
Selamanya aturan dan urusan antara Nakhoda dengan Sultan berlangsungan dengan baik sehinggalah ada khabar mengatakan Nakhoda mula berniaga dengan pedagang Inggeris. Datanglah Belanda menempatkan askarnya sebagai pemantau di daerah ini. Seorang komander Belanda datang dan menyoal Nakhoda, yang juga dipanggil sebagai Kyai Demang:
“…maka komander berkata: ‘Hamba menyuruh memanggil Kyai Demang akal hal bicara perahu yang dua buah lalu di Bengkulu itu. Tiada hamba tahu kepada orang itu melainkan hamba tahu kepada Kyai Demang saja. Kepada bicara itu, tiada salah orang itu, semuanya salah Kyai Demang. Mengapa tiada Kyai Demang tegah? Di dalam fakir hamba pasti Kyai Demang menyuruh perahu itu ke Bengkulu. Melainkan Kyai Demang hamba denda dua ratus rial sebab bicara itu.’ Serta didengar Kyai demang kata komander itu, maka baginda berkata: ‘Ya Tuan Komander, akan hal bicara itu, tiada hamba menyuruh perahu itu ke Bengkulu. Meski apa hukum tuan komander, hamba tanggung, jikalau hamba yang menyuruh perahu itu.’ Maka kata komander: ’Tiada boleh Kyai Demang Purwasedana melawan bicara hamba ini, melainkan bawa rial dua ratus kepada hamba pagi-pagi.’
Begitulah suara angkuh penguasa kolonial yang sesuka memerintah dan menindih bangsa yang mereka anggap wajar dikawal dan disuruh-suruh.
Denda besar ini dibayar dan diperintahkan Demang ini untuk membawa beberapa askar Belanda ke Semangka untuk ditempatkan ke balai kawalan. Malah beliau diperintah untuk membina balai kawalan ini seakan-akan suatu perintah kerah atau kerja paksa yang sering diperintah oleh penguasa feudal ke atas massa Melayu.
‘Maka Kyai Demang pulanglah ke Semangka membawa Holanda lima orang dengan perempuan satu. Serta sampai di Semangka diperbuatkan rumah, semuanya belanja Kyai Demang dan segala Melayu di dalam Semangka itu menolong membuat rumah itu serta dengan kampungnya seperti patut. Dan lagi bicaranya koperal itu terlalu keras. Barang apa disuruhnya buat, jikalau lambat, maka sudah pasti dipukulnya. Ada empat orang-orang Melayu dipukul koperal sebab membuat rumah itu lambat sudahnya.
KUASA KOLONIAL
Begitulah bengis dan biadap penguasa kolonial. Inilah juga keganasan yang mereka lakukan dan karya tua seperti ini merakam sebuah pengalaman sejarah yang sepatutnya anak bangsa hari ini faham akan keganasan penjajahan.
Demang atau Nakhoda Muda akhirnya ditangkap bersama dengan empat anak lelaki beliau. Harta benda beliau dirampas dan mereka akan dibuang ke tempat lain, besar kemungkinan juga dijual sebagai hamba.
Empat anaknya itu merancang untuk melepaskan diri kerana tidak rela diperlakukan Belanda. Baiklah mati dari dijual sebagai hamba. Selepas empat hari diseksa, akhirnya mereka mengamuk dan membunuh beberapa pegawai Belanda.
Mereka terus keluar dari Semangka, bersama 400 orang Melayu yang pastinya tidak rela dengan kekejaman Belanda. Mereka berjalan darat menuju ke Bengkulu kerana daerah itu di bawah naungan Inggeris.
Sebelum meninggalkan Semangka, Nakhoda menulis surat kepada Sultan Banten. Dengan nada kecewa akan layanan ganas oleh Belanda betapa beliau sepanjang hayatnya sedia berkhidmat kepada Sultan:
“Ini surat daripada Kyai Demang Purwasedana di dalam tanah Lampung Semangka sampai kepada tuan komander dan tuan Sultan. Akan hal Kyai Sultan serta dengan anak Melayu di dalam Semangka, semuanya berjalan meninggalkan tanah Semangka, daripada tiada tertanggung oleh kami sekalian perbuatan Holanda. Siapa tahu urdi tuan atau bukan, hamba diperbuatnya seperti anjing sahaja dan segala harta hamba dirampasnya dan hamba dikurungnya dan rumah hamba ditunggunya. Adapun di dalam fakir hamba tiada hamba berhutang kepada tuan Sultan atau kepada Kompeni, meski satu keping tembaga tiada hamba berhutang! Adapun di dalam Semangka ini menumpang di tanah tuan Sultan dan Kompeni, mencari kehidupan hamba daripada sekeping dua keping tiada hamba membuat yang salah selama-lamanya. Melainkan hamba minta ampun, tiada lagi hamba menyembah tuan lagi dan tiada hamba mengadap Kompeni Holanda lagi.”
Begitulah pendirian Nakhoda yang berani tidak mahu lagi tunduk kepada kuasa yang kejam. Beliau dan pengikutnya akhirnya berhenti di Kerui dan dibenarkan membuka petempatan di bawah lindungan Inggeris.
Beginilah cerita nasib Nakhoda Muda yang pada tingkat kemakmurannya sebagai pedagang lada hitam dicemburi oleh Belanda, mungkin juga oleh Sultan Banten. Layanan kejam yang diberikan kepada beliau memperlihatkan bahawa penjajahan masuk dengan segala macam licik memecahkan percaturan kuasa dalam kalangan penguasa pribumi.
Yang lebih ketara ialah kuasa ekonomi pribumi harus dikawal dan dilumpuhkan dan dengan itu kuasa kolonial dapat membolot setiap segala.
Derita yang harus ditanggung cukup besar. Begitulah yang tersemat dari pantun kiasan penutup dalam hikayat ini yang berbunyi:
“Tinggi gedung di Pulau Pinang
Pancuran di atas bukit
Baik-baik tuan bertenggang
Sengasara bukan sedikit”
Pembaca yang prihatin akan dapat merasakan penderitaan, kehilangan dan kerugian sebuah keluarga yang terbanding ini.
Namun semua musnah dan mereka harus membina hidup baru di daerah lain. Juga yang dapat kita kesan ialah sebuah maruah hidup yang harus dipertahankan betapa ia sangat mahal. Begitulah pepatah yang menyebut: “daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.” Yakni dari menanggung aib, baiklah mati. Dengan berani mengamuk mereka terlepas dari penderaan Belanda walaupun belum pasti mereka akan terselamat selepas itu.
Lembaran yang ditulis ini adalah rakaman berharga dari seorang pribumi yang menyaksikan keganasan kolonial. Walaupun mereka mendapatkan lindungan di daerah di bawah naungan kompeni Inggeris, perlu diingat kelicikan dan keganasan Inggeris jangan dianggap kurang daripada yang dilakukan Belanda.
Menarik dibaca nanti dalam “Syair Potong Gaji” oleh Tuan Simi yang menceritakan kegundahan dan keperitan kuli dari Bengkulu yang bekerja untuk kompeni Inggeris di Singapura. Mereka dilayan buruk dengan upah rendah, sehingga disebut “Beberapa lamanya bekerja sudah/Harganya dinilai setimbang ludah".
Penjajahan datang dengan keganasan dan diayah pemunahan fikiran anak negeri bahawa yang datang memerintah bangsa pribumi adalah manusia sakti dan bakti untuk mencerahkan mereka.
BUKA MATA, MINDA ANAK MUDA
Membaca karya sebegini seharusnya dapat membuka mata dan fikiran kita.
Lembaran “sastera” seperti karya ini harus dapat dibaca dari sudut sejarah rakyat, yang merakam kehidupan dan pengalaman mereka.
Sayang sering kali karya sebegini, termasuk juga karya-karya Munshi Abdullah dibaca dari lensa sasterawinya saja, sehingga pemikiran, kritikan dan gagasan yang terkandung di dalamnya terlepas dari kupasan dan penghargaan.
Warisan karya sebegini sebaiknya dapat dibaca oleh generasi muda yang melihat bahawa pemahaman akan sejarah dan pengalaman bangsa/manusia yang terdahulu seharusnya menjadi iktibar untuk kita berdepan dengan tantangan kini dan masa hadapan.
Kesadaran kita akan keganasan kolonial, termasuklah keganasan feudal, harus meingatkan kita betapa kekuasaan mutlak sanggup menggunakan kekerasan dan kehalusan untuk menundukkan fikiran dan perbuatan kita.
Maka membaca karya-karya sebegini wajar diperkembangkan. Wacana dan akses karya perlu ada. Menarik diperhatikan karya ini pernah diterbitkan di Singapura pada 1900 oleh Haji Muhammad Siraj di Kampung Gelam.
Sayang sekali karya ini tidak mendapat perhatian inteligensia Melayu di Singapura yang banyak memanfaatkan teks-teks Melayu lama yang kemudian diubah wahana menjadi filem-filem Melayu yang dihasilkan di Jalan Ampas, Singapura. Sekiranya teks “Syair Lampung Karam” yang dibaca meluas dalam masyarakat Melayu, sehingga akhirnya dijadikan filem pada 1967, Hikayat Nakhoda Muda ini tidak pula mendapat perhatian, mungkin kerana edarannya dalam bentuk bukunya tidak meluas.
Apapun syukur apabila karya ini diterbitkan kembali oleh Yayasan Karyawan di Malaysia pada 2018. Moga ke depan bacaan kritis terhadap karya-karya Melayu dapat diwacanakan terus, dan karya ini pastinya salah satu yang harus diberikan perhatian.

MENGENAI PENULIS:
Dr Azhar Ibrahim Alwee ialah Pensyarah Pengajian Melayu di Universiti Nasional Singapura (NUS). Selain kesusasteraan klasik dan moden Melayu, fokus penyelidikan beliau adalah wacana penulisan kritikal dan pembangunan intelektual Melayu-Indonesia.
Ikuti perkembangan kami dan dapatkan Berita Terkini
Langgani buletin emel kami
Dengan mengklik hantar, saya bersetuju data peribadi saya boleh digunakan untuk menghantar artikel dari Berita, tawaran promosi dan juga untuk penyelidikan dan analisis.



